
KASUS kebohongan Ratna Sarumpaet membuat panggung politik Indonesia yang jenaka jadi makin jenaka. Yakni kejenakaan yang serba mengenaskan dan karena itu menjengkelkan. Bukan hanya mereka yang berada di atas panggung. Orang-orang yang berseliweran di seputaran panggung, para penonton, juga makin menunjukkan bakat serupa. Beberapa di antaranya bahkan jauh lebih jenaka, padahal mereka sama sekali bukan komedian.
Ini ambiguitas yang kompleks. Secara teoritis, melawak tak mudah, tetapi faktanya negeri kita melahirkan lebih banyak pelawak dibanding, misalnya, ilmuwan. Apakah buruk? Bisa buruk bisa tidak, tergantung dari sisi mana memandangnya. Namun satu yang pasti, humor dan kejenakaan yang merupakan modal para komedian memang bukan hal yang bisa dipandang remeh. Humor dan kejenakaan, sebaliknya, harus disikapi serius agar berhasil.
Dalam tulisan berjudul “Humor Itu Serius” yang dimuat Harian Kompas pada 9 Agustus 1977, Arwah Setiawan, memaparkan teori‑teori tentang humor yang alih-alih menghadirkan tawa justru membikin kening jadi berkerut. Menurut Setiawan, humor tidak berhenti setelah tawa meledak. Humor bisa berumur lebih panjang, memberi pengaruh, karena memiliki daya guna sebagai kritik sosial, di mana dia berfungsi memperbaiki kekeliruan dan melepaskan ganjalan.
Paparan Setiawan selaras pendapat Arthur Koestler, penulis Inggris kelahiran Hungaria, yang menyebut kedudukan humor setara dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam tiga wilayah kreativitas. Alasan Koestler, ketiganya sama‑sama mencari analogi tersembunyi, walau kemudian berakhir dengan cara berbeda.
Satu di antara humor paling populer dan paling banyak mendapat sambutan adalah humor politik. Bob Hope, komedian Amerika Serikat, menyebut humor politik adalah bagian penting dari demokrasi. Pada tahun-tahun akhir Perang Dunia Kedua (1939-1945), humor-humor politik Hope menjadi warna tersendiri dari peristiwa mengenaskan itu. Lelucon-lelucon Hope merangsek, lalu mengemuka sebagai opini berbeda yang memberi masyarakat sudut pandang lain dalam melihat perang. Tahun 1974, saat Watergate, mega skandal yang sedang dikupas Washington Post ramai diperbincangkan, Hope juga ikut berpendapat. Kalimatnya yang satir, “Watergate gave dirty politics a bad name“, mendapatkan tempat dalam sejarah Amerika Serikat selain kejatuhan Richard Nixon.
Setelah era Bob Hope, humor politik kian kencang berkibar melalui nama-nama seperti Woody Allen, Robin Williams, Lewis Black, Jerry Seinfeld, Whoopi Goldberg, Ellen DeGeneres, atau Amy Schumer. Pada musim kampanye Presiden Amerika edisi mutakhir yang dimenangkan Donald Trump, humor politik melesat-lesat di berbagai acara televisi. Berdasarkan survei perusahaan analisa siaran televisi Jumpshot, pada hari-hari menjelang pencoblosan, warga Amerika Serikat justru meninggalkan acara-acara debat serius dan beralih ke bincang-bincang satire. The Late Show with Stephen Colbert berada di peringkat pertama, disusul The Daily Show with Trevor Noah dan The Tonight Show with Jimmy Fallon.
Dari dalam negeri ada Warkop (Rudi Badil, Nanu Mulyono, Kasino Hadiwibowo, Wahjoe Sardono, dan Indrodjojo Kusumonegoro) yang memulai jejak mereka sebagai komedian politik lewat program obrolan yang serba ugal-ugalan di Radio Prambors. Kemudian bisa dicatat nama Teater Koma, Butet Kertarajasa, dan yang terkini, Pandji Pragiwaksono dan Lies Hartono alias Cak Lontong. Namun pencapaian tertinggi humor politik Tanah Air sesungguhnya justru datang dari level politik paling tinggi pula, yaitu Presiden Republik Indonesia, presiden keempat, KH Abdurrahman Wahid.
Gus Dur, sapaannya Kyai Wahid, memang punya selera humor kelas wahid. Darinya lahir sangat banyak humor politik yang cerdas, canggih, dan melegenda saking lucunya. Gus Dur bahkan tetap melawak dalam keseriusannya. Silakan periksa buku kumpulan kolomnya yang bernas, Melawan dengan Lelucon (2000)
Persoalannya, yang lebih sering mengemuka di negeri terkasih kita hari-hari belakangan bukanlah humor politik model begini. Bukan kejenakaan yang lahir dari landasan emosi yang terkendali dan terkalkulasi. Sebaliknya, emosi yang mendasarinya sangat agresif, liar, dan berakibat tak lagi menjadikan logika sebagai tolok ukur. Humor, lelucon, “segila” apapun tetap harus berpijak pada landasan ini, tak boleh ngawur.
Sekarang yang menyeruak justru kengawuran-kengawuran. Justru logika-logika yang terjungkirbalikkan. Kebohongan Ratna Sarumpaet menjadi komoditi yang aktobatik. Ratna jelas-jelas berbohong dan ini sudah diakui secara terbuka. Namun kemudian, kebohongan ini dikemas sedemikian rupa, dipilin pelintir, dikocok, dilambung-lambungkan, hingga terkesan setara dengan hal lain yang diyakinkan tiada kalah gawatnya, yakni janji-janji kampanye Jokowi. Janji-janji belum terwujud yang sebelumnya telah dimunculkan melalui beragam meme. Kebohongan Ratna yang sifatnya personal disebut tidaklah seberapa aduhai dibanding kebohongan Jokowi.
Perkembangan kasus ini, yang membuat sejumlah orang yang ditengarai menyebarkan kebohongan terancam ikut diperiksa polisi dan termungkinkan mendapat sanksi hukum, memperlebar cakupan kengawuran. Para pencetus kengawuran menyebut orang-orang yang menyebarkan kebohongan sebagai korban Ratna Sarumpaet. Dengan demikian, apabila mereka mendapat hukum, maka seluruh rakyat Indonesia juga harus dihukum lantaran telah termakan kebohongan Jokowi.
Kubu Jokowi, atau barangkali katakanlah pihak-pihak yang secara sadar menempatkan diri sebagai pendukung dan akan memilih Jokowi di Pemilu Presiden 2019, tentu saja tidak mau kalah. Kengawuran perihal kebohongan dijawab dengan ide mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai Hari Antihoaks Nasional. Tanggalnya 3 Oktober, yaitu tanggal di mana Ratna Sarumpaet membuat pengakuan dan menyebut kebohongannya antara lain terjadi karena dia dibisiki setan. Ratna sendiri diberi gelar Ibu Hoaks Indonesia.
Begitulah, persis tingkah polah Lloyd Christmas dan Harry Dunne dalam Dumb and Dumber, kubu-kubu yang saling berseteru memang sudah sepenuhnya kehilangan kesungkanan untuk memamerkan ketololan. Mereka membuat kejenakaan-kejenakaan yang seyogianya masih potensial menerbitkan tawa itu jadi kehilangan greget dan sama sekali tak lucu.
Dimuat Harian Analisa
Kamis, 25 Oktober 2018
Halaman 20
Dimuat juga di http://www.analisadaily.com
http://harian.analisadaily.com/opini/news/politik-indonesia-dan-perkara-perkara-jenaka/638868/ 2018/10/25

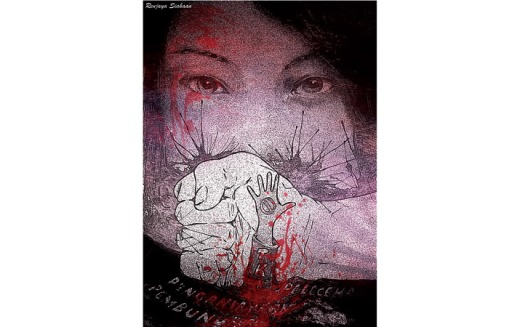 SUPAYA tidak jadi membingungkan kuberitahu kepadamu bahwa Mira Marcela, Anamira Isnaini Khadijah, dan Nur Asiah Jamil, adalah nama orang yang sama. Nur Asiah Jamil nama lahir. Anamira Isnaini Khadijah nama pengganti dan tertera di KTP dan berbagai kartu identitas dan nama inilah yang kau baca di halaman-halaman koran sejak beberapa hari lalu.
SUPAYA tidak jadi membingungkan kuberitahu kepadamu bahwa Mira Marcela, Anamira Isnaini Khadijah, dan Nur Asiah Jamil, adalah nama orang yang sama. Nur Asiah Jamil nama lahir. Anamira Isnaini Khadijah nama pengganti dan tertera di KTP dan berbagai kartu identitas dan nama inilah yang kau baca di halaman-halaman koran sejak beberapa hari lalu.

 SAYA tidak ingat persis kapan tepatnya saya bersentuhan dengan tuak. Saya hanya ingat satu momentum, waktu itu saya masih berseragam putih merah, masih SD, di pinggiran Kota Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, dan seorang tetangga meminta saya membelikan minuman itu ke lapo (kedai). Dengan uang yang ia berikan, tertebuslah tuak sebanyak satu teko.
SAYA tidak ingat persis kapan tepatnya saya bersentuhan dengan tuak. Saya hanya ingat satu momentum, waktu itu saya masih berseragam putih merah, masih SD, di pinggiran Kota Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, dan seorang tetangga meminta saya membelikan minuman itu ke lapo (kedai). Dengan uang yang ia berikan, tertebuslah tuak sebanyak satu teko.



